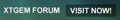Selama tiga hari aku mengeram diri di dalam kamar sempit yang beberapa bulan ini menjadi rumahku. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan harus membolos dari tempat tugas sebagai librarian, dengan alasan tidak sehat. Belakangan kondisiku terus menurun karena muntah terus menerus akibatnya berat badanku drop drastis.
Teman-teman baikku dari negara lain yang sa ma-sama bertugas di sini mencoba menjenguk; tapi ketukan mereka tak pernah kujawab. Pada atasan yang mengurusi karni, aku mengirimkan sebuah email, menjelaskan kondisi fisik yang tidak sehat.
Seharian kerjaku hanya meringkuk di tempat tidur, terkadang duduk di belakang komputer dan melihat foto anak-anak. Melihat senyum mereka, perasaan sentimentilku makin parah. Hhh, sejujurnya aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, membayangkan hari-hari di masa depan…
jika harus terbang dengan sebelah sayap.
Kucoba menenangkan hati. Kubuka I-tunes music library kuklik shuffle untuk mendengarkan lagu secara acak, dan apa yang kudengar makin memperparah perasaanku, Khianati…
Teganya dirimu mengkhianati
Walau kupastikan kelak kau mohon aku Pinta aku, untuk kembali padamu, lagi… (Keris Patih, Cinta Putih) Hatiku terasa kosong. Air mata mulai menitik. Entah kenapa pula setelah itu semua lagu seolah mewakili kedukaanku. Seperti sebuah lagu yang terselip di antara email-email menghibur yang dikirimkan teman-teman
When the day is long and the night,
the night is yours alone,
When you’re sure you’ve had enough of this life,
well hang on,
don’t let your self go,
’cause everybody cries
and everybody hurts
sometimes
Lirik The Corrs ini malah membuatku menangis makin keras.
Selama beberapa hari itu aku mencoba melihat ke belakang.
Kepergianku, suamilah yang mendorong hingga aku yang awalnya ragu, akhirnya mempunyai keberanian. Dia juga yang membelikanku berbagai keperluan agar hidupku di negeri orang tidak sepi. Benarkah itu semua agar aku enyah dan mereka bisa berduaan sepuasnya?
Pikiran buruk itu sulit kutepis. Apalagi mengingat begitu sulit menghubungi telepon genggamnya. Pernah sampai 16
kali aku mencoba menelpon tidak satu pun tembus. Email-email nyaris tidak pernah dibalas. Padahal banyak dari email yang kukirimkan kutujukan untuk anak-anak, agar mereka tetap merasa mamanya tidak pernah meninggalkan.Aku ingat pernah menangis ketika menyampaikan betapa aku nyaris frustrasi dengan sikapnya yang kurang peduli.
Saat itu Mas mencoba rnenenangkanku, dengan alasan sibuk sekali. Bahkan mencek keluar masuknya dana dari rekeningnya pun dia tak sempat lagi. Dulu aku menerima saja jawabannya, tetapi sekarang? Kesedihan perlahan berganti warna menjadi kemarahan. Bagaimana bisa dia menjawab seperti itu?
Aku kalah penting oleh rekening? Yang benar aku kalah oleh perempuan itu!
Marah, kecewa, sedih… menangis.
Hanya saat menerima telepon ibu, aku menggigit bibir kuat-kuat agar tangis tidak tumpah. Tidak mungkin aku menambah kesedihan Ibu yang seperti adikku sudah lebih dulu menangis karena khawatir akan kondisiku.
Tapi aku tahu, tidak boleh membiarkan diri hanyut dalam kesedihan. Aku harus bangkit, sebab dengan begitu aku bisa memikirkan keputusan yang terbaik. Dan untuk anak-anak aku harus sehat.
Hari ketujuh, meski dengan wajah sembab, aku meninggalkan apartemen, dan berputar-putar tidak tentu arah dengan bis hingga larut malam. Hari berikutnya aku mengunjungi toko buku terbesar dan menghabiskan waktu berjarnjarn sebelum pulang dengan mengantongi buku: He’s just not that into you!
Isinya membuatku berpikir, apa yang sebenarnya masih aku dan suami miliki? Masih banyak kah yang tersisa?
Bisakah di perbaiki? Mungkin saja aku subjektif, tetapi jika merujuk pembahasan buku dan ciri-ciri yang disebutkan, mataku seperti terbuka… begitu banyak poin yang digambarkan yang membuatku berpikir, barangkali sudah cukup lama sebenarnya aku kehilangan suamiku. Sejak pengkhianatan pertamanya? Anyway, at least he hasn’t been that into me for three years!
Apalagi suamiku, menurut penuturan keluarga si gadis berdasarkan update dari mereka, konon akan menikah.
Bahkan berulangkah si gadis mendesak agar suami tidak perlu menunggu kepulanganku.
Allah…
Kutahan keinginan untuk melabrak suami di telepon, sebab aku tidak ingin bicara dalam kemarahan. Kesedihan kucurahkan dalam sujud-sujud shalat malam, dan mengaji.
Aku berharap dengan mendekat kepada Allah,aku bisa kuat menerima apa pun bentuk penyambutan kepulanganku nanti. Bahkan jika suamiku memutuskan untuk menikahi gadis itu.
Jika itu yang terjadi, aku harus siap.
Ya, selama anak-anak, sumber kebahagiaanku berada di sisi.
Sayang, Mama akan mengajak kalian terbang tinggi, meski hanya dengan satu sayap.
(Berdasarkan kisah Tania, Japan)
Lagu Kelabu
“Aku harus menjaga otakku tetap sehat, waras, sebab dibutuhkan untuk mengatur strategi agar bisa keluar dari situasi buruk ini! ”
Dengan visa turis kami berdua, aku dan anakku, terbang menuju Negeri Kincir Angin, tepatnya 29 Juni 1986.
Esoknya kami tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Ya, inilah negeri bangsa kolonial. Pada zaman revolusi, ayahku bersama pasukan pejuang pernah menyabung nyawa, melawan Belanda.
Sekarang, di sinilah aku dan anakku, putri dan cucu seorang pejuang ’45. Demi mengadu nasib, demi meraih masa depan, demi melacak jejak surga yang kudamba.
“Ya Tuhanku… kami mohon. Lindungilah kami berdua, lindungilah,” desisku mengambang di udara musim panas negeri asing.
Beberapa saat aku menghirup aroma Negeri Kincir Angin sebanyaknya-banyaknya, seluas paru-paruku mampu menampungnya. Berharap bahwa ini ha nya mimpi belaka yang segera terbangun, kemudian kutemukan anakku berada di ruang keluarga yang nyaman tempat favoritnya asyik bermain-main. Namun tidak, ini adalah sepenggal awal perjalanan me lacak jejak surga!
“Mama… dia siapa?” suara mungil anakku merenggut seluruh khayal dan kenyataan yang sempat nyaris tak bisa kubedakan lagi.
Aku tersentak, mengikuti telunjuk mungil yang mengarah kepada seorang lelaki bule. Sosok itu, ya, ternyata berwajah keras, terkesan angkuh dan show-off dalam berbusana. Ini persis sekali dengan mantan suami.
Seketika ada yang berdesiran dalam dadaku, sesuatu yang seharusnya kumaknai sebagai pertanda buruk.
Lelaki itu, Gez, menghampiri kami diikuti oleh beberapa orang yang diperkenalkannya sebagai keluarga besarnya.
Dia menyalamiku, tepatnya menciumi pipi-pipiku dengan atraktif. Apabila tak kucegah dengan gerakan tegas, bibirnya memaksa akan mencium bibirku saat itu juga.
“Yeah… inikah jagoan kecilmu, hem?” ujarnya seraya hendak memangku anakku dengan gerakan kasar.
“Mama… gak mau!” protes Peter spontan menghindarinya, berlari dan bersembunyi di balik tubuhku sambil memegangi ujung blazerku.
Aku bisa melihat perubahan pada raut wajah Gez, perpaduan antara geram dengan hasrat menguasai. Dia berhasil mengekang dirinya dengan bersikap santun terhadap diriku, penyayang terhadap anakku. Empat lelaki dan tiga perempuan, keluarganya itu, berusaha pula menyambut kami bedua dengan ramah dan sukacita.
“Nah, kita berpisah di sini,” berkata Gez saat berada di parkiran. “Mereka akan pulang ke apartemen masing-masing dan kita… Yeah, kita harus segera menyelesaikan urusanku!”